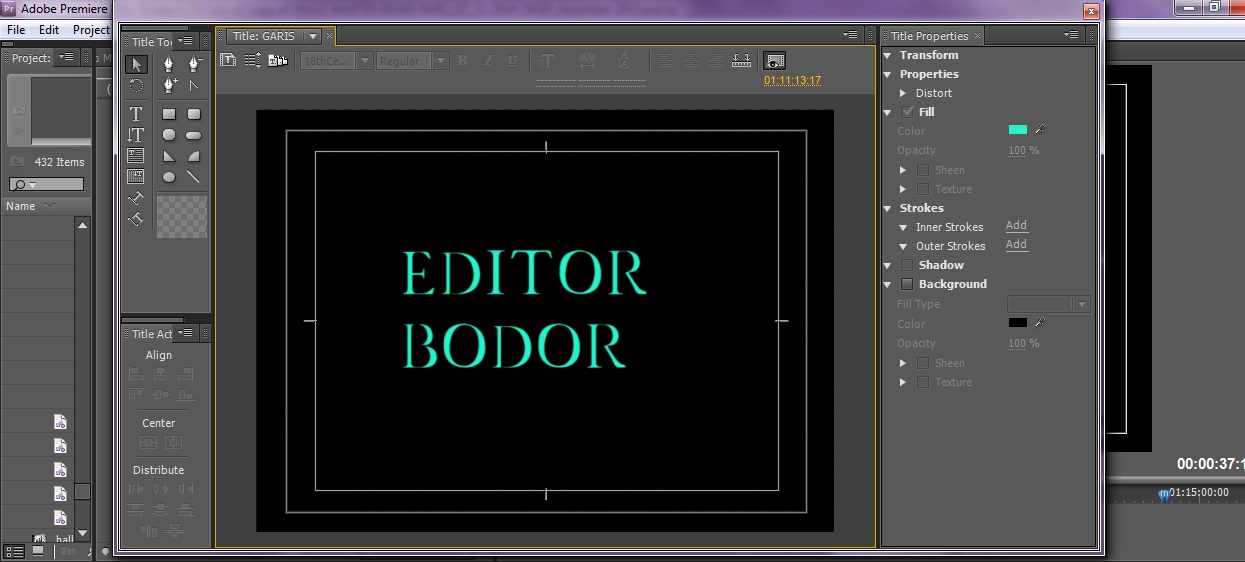Selasa, 19 April 2016
Cerpen: Ujung Hutan
Wira tak mampu menutupi rasa malunya. Hanya duduk menunduk di tengah balai sidang. Dadanya disesaki oleh sesal. Ia merasa semua mata mentap dengan benci, kecuali, mungkin, kedua orang tuanya.
Hampir semua warga desa hadir dalam sidang. Para tetua, pemuda, sampai anak-anak. Mereka yang tak kebagian duduk di kursi kayu, duduk di anak tangga, di setiap sisi balai yang bertatap, berubin, namun tak berdinding itu. Dalam sidang ini, bahkan anak-anak tak ada yang berani bercanda. Semua orang menutup mulut, kecuali mereka yang berhak bersuara.
“Wira melakukan dosa besar! Ia telah mencuri!” kata Abah Una sambil menujuk Wira. Sorot matanya tajam wujud ketegasan.
Ayah Wira menggeleng. “Anakku bukan mencuri, Abah Una! Dia hanya membawa apa yang tertinggal dari mahasiswa yang melintasi desa.”
“Membawa masuk barang milik orang lain saja sudah sebuah kesalahan, Kuswan!” ujar Abah Una. “Bisa saja itu adalah barang yang berbahaya!”
Suasana jadi besik karena warga saling bisik. Mereka menyadari bahaya besar akibat perbuatan Wira. Sudah banyak mahasiswa atau polisi hutan melintas desa selama ini. Tak ada satu pun yang berulah. Perbuaatan Wira bisa mengubah segalanya.
Berisiknya warga membuat wajah Wira semakin merah. Ia tak mampu melihat wajah orang-orang, terlebih lagi orang tuanya. Ia yakin ibunya sedang menahan tangis, atau bakan amarah.
Ki Agum tiba-tiba berkata dengan wibawa. “Coba tunjukan benda yang dibawa Wira.” pintanya dengan sopan. Salah seorang pemuda bangun, memberikan benda itu pada Ki Agum. Semua mata ikut melihat. Benda itu kotak, biru, cukup kecil untuk bisa digenggam, dan tesambung dengan rantai kecil yang menggantung.
“Ada yang tahu nama dan guna benda ini?” tanya Ki Agum sambil melihat sekeliling. Tak ada yang menjawab, hanya menggeleng.
“Jika kita tidak tahu guna benda itu, bagaimana kita menganggapnya berbahaya?”, ujar Kang Kuswan, membela anaknya.
“Justru, karena kita tidak tahu, bagaimana kita menganggapnya tidak berbahaya?” balas Abah Una dengan sinis. Wira bisa melihat dengan lirikan, banyak orang mengangguk, lebih percaya pada perkataan Abah Una ketimbang ayahnya.
“Kita tidak mungkin menganggap tindakan Wira bukan kesalahan, karena tak ada benda asing yang boleh masuk ke desa kita.” kata Ki Agum. “Kita hanya bisa memutuskan kadar kesalahannya.”. Keringat Wira mulai keluar dari samping kepalanya, membayangkan dirinya sampai menjalani hukuman berat. Kesalahan besar berarti hukuman berat.
“Malam ini juga, hukuman akan diputuskan oleh para sesepuh.”, tambah Ki Agum. Kedua tangannya memberi isyarat agar para sesepuh lain mendekat padanya. Sepuluh sesepuh lain, termasuk Kang Kuswan dan Abah Una menuruti isyarat Ki Agum. Mereka setengah berbisik memberi suara. Semua warga desa berusaha mencuri dengar.
Ki Agum melangkah lebih depan dari sesepuh lain. “Ringan.” ucapnya tegas. “Wira kami jatuhi hukuman mengurus kebun desa selama satu bulan. Semoga Wira tidak meremehkan kesalahannya. Dan ini menjadi pelajaran bagi warga yang lain.”
Ucapan itu membuat para sesepuh membubarkan diri dalam iringan keriuhan suara warga. Beberapa warga mengangguk, beberapa menggeleng, setelah mendengar keputusan itu. Abah Una melangkah dengan cepat dengan raut kecewa.
Kang Kuswan dan Nyai Diah mendekati anaknya yang masih menunduk. Wira tak bisa menahan diri untuk tidak memeluk ayahnya sebagai ganti terima kasih.
“Berjanjilah kamu tak akan melakukan itu lagi.” sambung Kang Kuswan, sangat dekat dengan telinga anaknya. “Aku berjanji, ayah!” ucap Wira tegas. Ia sangat tahu, tak boleh ada lagi penasaran terhadap benda asing milik orang lain dari luar desa.
Malam itu adalah tidur nyanyak pertama Wira sejak seorang anak memergokinya membawa benda kotak berwarna biru. Benda yang hampir saja membuatnya dalam bahaya besar.
Tiga hari sudah Wira melaksanakan hukuman. Seorang diri menggarap kebun desa. Hukuman yang membuat warga lainnya punya waktu berlibur bersama keluarga. Meski sendiri, semua terasa ringan jika ia membayangkan hukuman berat yang hampir menimpanya.
Wira tak lagi sendiri. Seseorang datang dari balik pepohonan. “WIRA!”, teriak sesorang lelaki dari kejauhan, membuat burung-burung di pepohonan beterbangan. Wira mendekat, tahu bahwa itu adalah Surya, teman sebayanya.
“Ada apa?” tanya Wira penasaran. Surya tak langsung menjawab. Ia memberi tatapan sinyal keprihatinan. “Ada apa?” ulang Wira lebih keras.
“Kamu ditunggu di balai warga.”, jawab Surya.
“Memang ada apa?”
Surya hanya menggeleng meski tahu. Dan ia tetap tak mau menjawab sepajang perjalanan. Wira malah mendapati kerumunan orang di sekitar balai sidang. Ia tak mampu menebak apa yang akan menimpa meski telah sampai ke desa. Wira masuk ke balai sidang, melewati orang-orang yang menatap sinis.
Balai sidang lebih ramai dari sidang lalu. Wira melihat mata ibunya yang sembab dan basah. Ayahnya bahkan tidak mau melihat ia melintas. Abah Una membalik tubuhnya ketika tahu Wira sudah tiba. Ia menatap Wira tanpa belas kasih.
“Aku sudah tahu benda yang kau bawa ini!” Abah Una setengah berteriak. “Biar pamong praja perbatasan ini yang mengatakan!” sambil menunjuk pada orang yang berdiri di samping Abah Una. Orang itu melihat sekeliling sebelum bicara, memastikan semua orang siap mendengarnya.
“Aku membawa benda itu ke perbatasan.” ucapnya lantang. “Aku menyamar agar bisa bertanya pada Polisi Hutan.”. Ucapan yang membuat warga desa berdesas-desus seketika.
“Polisi Hutan mengatakan bahwa benda itu bernama Ji Pi Es.” Sambung Si Pamong Praja. “Benda yang berguna sebagai peta. Benda yang bisa diketahui keberadaannya dari jarak yang sangat jauh.”
Bisik-bisik warga menjadi riuh seketika. Wira tiba-tiba merasa mual. Ia merasa badannya seperti mengkerut sekaligus lemas. Para sesepuh saling bicara, dan sesekali melihat ke arahnya. Ayahnya hanya diam seribu bahasa.
“Mohon tenang!” Ki Agum menghentikan keriuhan warga. Suara paling tinggi dari Ki Agum yang pernah Wira dengar selama ini. Ia tahu bahwa ada kemarahan dalam suaranya.
“Kami memutuskan untuk mengubah hukuman bagi Wira.”, katanya dengan tegas. “Ini akan menjadi pelajaran bagi semua warga.”
Suasana semakin riuh. Ki Agum memberi isyarat tangan agar semua berhenti bicara.
“Hukuman berat akan dijatuhkan.” ujar Ki Agum sambil memandang Wira. Pandangannya seperti meminta pemakluman akan ketegasan yang harus ia lakukan. Tangan Ki Agum menjulur dengan isyarat menunjuk ke arah luar balai warga, lalu berkata “Wira Diasingkan selama satu bulan!”
Meski Wira tahu itu akan terucap, tetap saja membuatnya sesak. Wira tahu bahwa diasingkan berarti keluar dari desa, segera setelah Ki Agum memberi isyarat pengusiran dengan telunjuknya.
“Pamong Praja akan mengantar sampai perbatasan, untuk memastikan kamu menjalankan hukuman dengan benar.” kata Ki Agum sambil melangkah keluar balai sidang. Itu sekaligus isyarat agar Wira segera melangkah meninggalkan balai, juga desa.
Wira tahu langkah para sesepuh dan warga menggiring langkahnya. Ia bisa mendengar beberapa ibu yang mengelus-elus anaknya sambil menasihati agar tidak bernasib sama dengan dirinya.
“Aku akan ikut mengantarmu sampai ujung hutan, Wira.”, ujar Surya yang mengikuti. Wira senang mengetahui Surya mau melakukan itu, meski ia berharap ayahnya yang akan mengantar ke perbatasan.
“Apa kamu yakin?”, tanya Wira menoleh ke belakang tanpa berhenti. “Ujung hutan itu sangat jauh.”
“Ya, aku yakin.”, jawab Surya. “Lagi pula, sudah lama aku tak ke sana.”
Wira tersenyum secukupnya. Kebaikan Surya cukup menghibur. Wira, Surya, dan Si Pamong Praja terus berjalan hingga melewati rumah terakhir. Mereka mulai menapak di jalan setapak.
“Wira!”, panggil ayahnya dari belakang punggung. “Ayah akan ikut mengantarmu.”, kata ayahnya, menyusul Pamong Praja dan Surya, menyamai kecepatan Wira. “Makanlah ini, Nak!”. Ayahnya memberi nasi lalap yang dibungkus daun pisang. “Aku tak mau makan sendirian.”, kata Wira, menahan diri, meski ia sempat melirik bungkusan itu.
“Makanlah dulu, Nak!”, Si Pamong Praja memberi saran. Surya mengangguk memberi dukungan. Kang Kuswan kembali menyodorkan. “Kami akan kembali ke desa setelah ini. Sedangkan kau mungkin harus berburu, memakan daging mentah di luar sana.”, Kang Kuswan memberi pengertian. “Kamu akan sangat membutuhkan tenaga.”
Wira kembali melirik bungkusan lalu berhenti. Ia menerima makanan itu dari ayahnya. Wira menduduki tonjolan akar pohon pada pinggiran jalan setapak untuk makan. Itu adalah makan siang terlambatnya, dan mungkin sekaligus makan malam. Wira memakan semua dengan lahap.
“Ingatlah nak, kemungkinan besar kamu akan bertemu dengan polisi hutan.” Ucap Kang Kuswa. “Mereka tidak akan melukaimu, karena mereka bertugas melindungi desa kita, meski secara tak langsung.”
Wira mengangguk-ngangguk sambil terus mengunyah. “Aku akan baik-baik saja, ayah.” tanggap Wira, lebih kepada usaha membuat ayahnya tidak khawatir. Ia tak ingin membebani lebih banyak lagi, meski tahu akan berada dalam bahaya.
Wira sudah membersihkan tangannya dari semua nasi yang menempel di jari tangan kanan. Keempatnya kembali berjalan. Tak ada lagi perhentian. Jalan setapak mulai menurun. Ujung hutan sudah terlihat.
Si Pamong Praja paling dulu mengehentikan langkahnya. Ia tidak mau lebih dekat lagi dengan perbatasan, namun terus mengikuti Wira dengan matanya.
“Jangan mudah marah jika melihat orang menebang pohon.”, kata Si Pamong Praja dari balik punggung Wira. “Mereka yang dari Perhutani, juga para polisi hutan, sudah punya perhitungan yang matang dalam menebang, agar hutan tetap lestari.”
Wira mengangguk. Ia sudah mendengar hal itu dari sesepuh desa. Juga tentang orang-orang Perhutani yang tahu akan keberadaan desanya. Kabarnya, mereka sangat menghormati keberadaan warga, meski tak semua dari mereka percaya.
Langkah Surya juga sudah berhenti. Wira bersiap kehilangan derap langkah sang ayah. Jantungnya semakin berdebar. Sulit baginya meninggalkan hutan di belakang. Berat baginya meninggalkan desa. Ia tak pernah mengerti, kenapa manusia bisa hidup begitu jauh dari hutan. Jauh dari kesejukan, keteduhan, dan suara satwa di dalamnya.
Suara langkah ayah sudah punah. Sekarang tinggal langkah kakinya. Wira menoleh, melihat tiga orang pengantarnya. Ayahnya menunduk, Surya pun demikian. Hanya Si Pamong Praja yang bertatap muka dari gundukan jalan setapak. Tatapan kewajiban, memastikan Wira melaksanakan pengasingan dengan wujud yang semestinya.
Wira berpaling, melangkah lagi menuju ujung hutan. Jalannya mulai membungkuk. Wujudnya mulai berganti. Ia tak mengira akan mengalaminya dua kali. Menjelma seperti pertama kali ia masuk ke dalam hutan. Ketika itu, ia memilih ikut bersama rombongan yang setia pada Kakang Prabu. Ia berharap kabar kesalahannya tidak sampai ke telinga rajanya itu, karena ia sangat malu.
=======
Cerpen ini menjadi juara III Kategori-C Lomba Menulis cerpen Green Pen Award 2016 yang diselenggarakan oleh Perum Perhutani.
Minggu, 20 Maret 2016
Pemikiran: DEMOKRASI, AGAMA, DAN PILKADA
Sebagaian orang mungkin merasa aneh
kenapa seorang-saya menganggap demokrasi tidak cocok dengan agama. Saya bilang
agama, bukan agama saya saja. Bahkan saya berani berpendapat bahwa demokrasi
itu memang dikonsep untuk melawan agama.
Bagi saya, agama adalah aturan
tertua. Apa yang disebut kearifan lokal, norma, dan adat istiadat pun,
sumbernya adalah agama. Logika ini sangat sederhana. Berhubung agama itu
jalan yang dibuat oleh Tuhan, lalu
apakah ada yang lebih awal dari Tuhan?
Makna paling mendasar dari demokrasi
adalah aturan yang sesuai kehendak mayoritas. Segala atribut-atribut lain yang
disematkan padanya tak lain hanyalah hiasan dan harapan akan sebuah keadaan.
Contoh-contoh atribut lain itu diantaranya: kesamaan hak, kebebasan
berpendapat, transparansi, atau trias-politica. Padahal, dengan makna demokrasi
yang mendasar dan sederhana tadi, kalau mayoritas berkehendak bahwa golongan
tertentu haknya lebih, ya itu tetap demokrasi. Atau kalau mayoritas berkehendak
tidak ada kebebasan berpendapat, ya itu juga demokrasi, begitu seterusnya.
Pokoknya tidak ada ciri lain selain aturan sesuai kehendak mayoritas. Sebanyak
apapun telur, ayam goreng, perkedel, dan brokoli, Indomie tetap hanya yang ada
di dalam bungkusnya saja. Lainnya, tambahan. Tak bisa kita katakan bahwa ayam
goreng atau brokoli adalah Indomie. Bagi yang tidak suka Indomie, silakan ganti
dengan Supermi, Sarimi, Mie Sedap, atau Mie Sukses isi dua.
Nah, dalam titik inilah demokrasi
terlihat bukan hanya tidak cocok dengan agama, tapi juga bermusuhan. Jika agama bicara tentang ‘harus’, demokrasi
bicara tentang ‘tergantung’. Jika agama bicara tentang hal-hal tertentu saja manusia
boleh menentukan, maka demokrasi menganggap bisa semuanya. Memang canggung
untuk langsung mengatakan demokrasi sebuah keburukan, melainkah sesuatau yang
berlebihan. Sesuatu yang berlebihan pasti buruk. Nah, tak lagi canggung.
Demokrasi memang sebuah konsep
pembablasan akan otoritas tunggal. Maka, tak ayal, beberapa orang menganggp
bahwa demokrasi adalah berhala. Buat saya, itu tidak lebay. Setidaknya sebuah
kisah di bawah ini bisa menjadi contoh bahwa kehendak mayoritas bisa menjadi jalan menuju pemberhalaan,
sekalipun di dalam masyarakat yang punya tradisi mengesakan Tuhan.
Atas perintah Allah, Musa menuju
bukit Thur untuk menerima mukjizat Taurat. Musa berencana pergi selama 10
malam, tapi kemudian digenapkan selama 40 malam. Sebelum berangkat, Nabi Musa
pun menitipkan Bani Israil pada adiknya, Nabi Harun. "Gantikanlah aku
dalam memimpin kaumku. Perbaikilah dan janganlah kamu mengikuti jalan
orang-orang yang membuat kerusakan," ujar Musa.
Harun pun kemudian memimpin Bani Israil. Namun, rupanya Samiri tak peduli dengan nasihat Harun. Ia pun mengajak Bani Israil untuk mengumpulkan segala perhiasan emas yang selama ini dibawa. Emas tersebut dikumpulkan untuk kemudian dilebur di atas api. Setelah emas meleleh, Samiri melemparkan tanah jejak kuda Jibril yang ia simpan selama perjalanan dari Mesir. "Jadilah anak sapi!" teriak Samiri girang tanpa merasa berdosa. Lupa sudah Samiri akan peringatan Musa agar tak menyembah berhala, tapi selalu mengesakan Allah.
Dengan kebodohan Bani Israil, mereka pun percaya dan mengikuti ajakan buruk Samiri. Alhasil, mereka pun menyembah patung anak sapi tersebut selama Musa pergi. Sementara, Harun tak sanggup melawan Bani Israil sendirian. (dari Republika online)
Harun pun kemudian memimpin Bani Israil. Namun, rupanya Samiri tak peduli dengan nasihat Harun. Ia pun mengajak Bani Israil untuk mengumpulkan segala perhiasan emas yang selama ini dibawa. Emas tersebut dikumpulkan untuk kemudian dilebur di atas api. Setelah emas meleleh, Samiri melemparkan tanah jejak kuda Jibril yang ia simpan selama perjalanan dari Mesir. "Jadilah anak sapi!" teriak Samiri girang tanpa merasa berdosa. Lupa sudah Samiri akan peringatan Musa agar tak menyembah berhala, tapi selalu mengesakan Allah.
Dengan kebodohan Bani Israil, mereka pun percaya dan mengikuti ajakan buruk Samiri. Alhasil, mereka pun menyembah patung anak sapi tersebut selama Musa pergi. Sementara, Harun tak sanggup melawan Bani Israil sendirian. (dari Republika online)
Jangankan ulama atau pemuka agama, rasul
yang masih hidup saja bisa ditentang oleh mayoritas yang menggunakan konsep ini.
Bayangkan! Dosa terberat, menyekutukan Tuhan saja bisa lolos, apalagi maksiat
lainnya. Karena yang penting itu kehendak mayoritas, tak ada urusan sekalipun dengan
utusan Tuhan. Jadi, tak lebay kan, jika demokrasi dianggap berhala?
Demokrasi memang disepakati untuk
menentang otoritas tunggal. Baik Tuhan, apalagi sekadar rasul, terlebih raja
dan ratu. Apa yang wajib bisa jadi pilihan, bahkan malah jadi terlarang, selama
mayoritas menghendaki demikian. Sebaliknya, sesuatu yang terlarang bisa jadi
boleh, bahkan wajib asal mayoritas menghendaki. Tak heran, di sebuah negara dengan
jumlah penduduk muslim terbanyak, dengan banyaknya ahli agama, majelis ilmu,
sampai majelis ulama, mengamalkan maksiat yang dosanya bekali-kali lipat dari
dosa menzinah ibu kandung, menjadi hal biasa. Gimana kurang musuhan dengan
agama coba?
Tak heran, di negara-negara yang
berhasil demokrasinya, ya pasti berhasil sekuler dan liberalnya. Judi jadi
industri. Zinah jadi industri. Mabok jadi industri. Riba jadi industri. Kalau
belum begini, ya belum berhasil demokrasinya. Negara-negara yang jajal fusion
antara agama dan demokrasi akan selalu jadi negara bimbang, labil, dan ngambang
kayak ‘itu’ di empang. Terombang-ambilng gelombang air karena tiupan angin.
Jadilah banyak aturan banci, yang memang setengah-agama-setengah-liberal,
setengah-taat-setengah-maksiat. Mau liberal terganjal agama, mau taat terganjal
selera massa.
Untungnya, itu bukan sebuah arti kesuksesan.
Bagi saya, sukses itu kalau kita berhasil cukup tanpa menentang falsafah hidup
tertinggi. Jadi, negara dengan industri maksiat, bisa jadi kaya, megah,
berlimpah, tapi dia tidak sukses. Kekayaannya pasti tidak menjadi berkah baginya
dan bagi tetangganya. Tak menjadi rahmat bagi seluruh alam. Terbayang nggak,
timpangnya Amerika dengan Afrika?
Tapi
demokrasi banyak menghasilkan aturan yang baik, loh.
Kebaikan itu sudah default
settingnya agama untuk manusia. Tuhan selalu membolehkan, bahkan mewajibkan kebaikan. Demokrasi
itu versi telat-klaimnya kebaikan hidup.
Nah, baru dah saya sambung-sambungin
ke hal aktual kekinian yang sedang hangat-hangatnya, bahkan panas-panasnya,
karena berhasil membuaskan banyak orang. Tentang bagaimana perhelatan demokrasi
dalam memilih kepala daerah yang menjadi ibu kota Indonesia gitu ganti.
Bagimana dalil agama dijadikan pertimbangan untuk tidak memilih salah satu
calon, karena calonnya: Kafir. Calonnya tidak seagama. Dalil ini wajar saja
jika ada dalam agama lain.
Masalahnya, dalil ini bisa dianggap berlebihan
dari sudut pandang demokrasi aktual. Muslim vs Kafir. Orang muslim haram memiih
orang kafir! Itu benar. Tapi kalau mayoritas orang muslimnya memilih demokrasi,
yang salah satu hasilnya, dengan kehendak mayoritas, membolehkan orang kafir
jadi pemimpin, ya itu resiko. Kalau kamu memilih iPhone, ya terima lambang
apelnya yang sudah terbelah, jangan minta diservice supaya apelnya utuh.
“Bang, ada iphone 11S yang apelnya
masih utuh nggak?”
Abang-abang iBox langsung resign.
Ya, tapi kan memilih orang kafir itu
haram! Dosa!
Yah, dia sekarang bicara dosa.
Memang demokrasi dikonsep untuk apa? Untuk berlomba-lomba mengumpulkan pahala?
Untuk mengajak pada kebaikan dan mencegah keburukan? Baca lagi dari awal
mendingan.
Bagi saya, yang patut disyukuri
dalam hidup ini, terkait keberadaan konsep demokrasi dalam hidup ini, adalah
bahwa, demokrasi bukan syarat bernegara.
Lebih bersyukur lagi, demokrasi bukanlah syarat menjadi manusia. Sangat bersyukur
lagi demokrasi bukan syarat untku bisa memberi dan menerima cinta. Paling
besyukur lagi, demokrasi bukan syarat untuk bisa masuk surga, yang semoga kita
berada di sana bersama-sama nantinya.
Pemikiran: Aher, Berita, dan Pilkada Jakarta + Syair Lagu Iwan Fals
Wah, apa hubungannya nih?
Beberapa hari terakhir saya
berulang baca berita tentang banjir di Bandung dalam tautan di bawah ini:
http://news.okezone.com/read/2016/03/15/525/1336279/banjir-bandung-aher-semoga-tuhan-enggak-turunkan-hujan-sekaligus
Berikut isi beritanya:
BOGOR - Menghadapi musibah banjir akibat
meluapnya aliran Sungai Citarum, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan menyerahkan
hal tersebut kepada Tuhan YME dan berharap hujan yang menguyur agar cepat
mereda dan banjir segera surut.
"Ya
kalo hujannya sudah engga ada, udah panas lagi ya pasti banjirnya otomatis reda
kan," katanya, saat menghadiri HUT Satpol PP ke 66 dan HUT Linmas ke 54 di
Lapangan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor, Selasa (15/3/2016).
Pria
yang akrab dipanggil Aher tersebut hanya berharap dan mengajak warga Bandung
khususnya yang dilanda musibah banjir untuk berdoa agar hujan yang turun mereda
dan banjir segera surut.
"Kan
sekarang masih musim hujan, mudah-mudahan kita berdoa kepada Tuhan ke depannya
hujan yang turun tidak sekaligus. Kalau hujannya sedikit juga banjir kecil
tidak sebesar ini," ungkapnya.
Sebelumnya,
lebih dari 10 ribu rumah di empat kecamatan yakni di Kecamatan Dayeuhkolot,
Bojongsoang, Bale Endah, dan Katapang. Kabupaten Bandung, Jawa Barat terendam
luapan Sungai Citarum sejak Sabtu 12 Maret 2016.
Selain
itu, luapan Sungai Citarum juga turut menggenangi ruas jalan utama penghubung
Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung.
Berita itu tentang komentar
Aher terkait banjir yang melanda daerah yang dipimpinnya. Dan berita itu menimbulkan
beberapa tanggapan, diantaranya seperti tergambar dalam tautan gambar. Komentar yang bawa-bawa sempaknya nggak usah dibayangin
ya. :D
Kenapa sampai ada orang
menganggap bahwa apa yan g disampaikan Aher itu salah, atau tidak baik, atau
tidak keren? Hingga timbul komentar neagtif sampai satire beserta memenya?
Hal itu karena tidak semua
orang sadar akan detail.
Yuk , kita ulas dari poin ke
poin hingga menjadi kesatuan yang utuh.
1.
Konteks.
Keterkatian
sangat penting agar kita bisa mengetahui pesan secara utuh. Dalam kasus ini,
Aher tentu menjawab sebuah pertanyaan. Dia bukan ujug-ujug ngomong seperti yang
menjadi kutipan langsung dalam berita di atas.
Nah,
dari jawaban Aher, apa kiranya pertanyaan dari wartawannya? Kita tidak bisa
menemukan hal itu karena memang tidak tertulis. Berita itu hanya menunjukan
bentuk umum dalam paragrap pertama bahwa Aher,
‘Menghadapi musibah banjir...’.
Bentuk
umumnya adalah ‘Menghadapi’. Tanpa rincian dalam tahap apa Aher menghadapi
banjir tersebut. Lalu bagimana kita tahu rincian pertanyaan wartawan kepada
Aher, dalam fase menghadapi banjir yang dimaksud? Itulah mengapa kita
memerlukan,
2.
Logika Waktu.
Sudah
saya sampaikan bahwa tidak semua orang sadar akan detail. Padahal, karena
detail lah hidup kita jadi indah dan penuh makna. :D
Jika kita melihat paragraph kelima, berita tersebut diawali dengan kata ‘Sebelumnya’. Kemudian menceritakan banyaknya rumah yang terendam beserta lokasi-lokasi banjir.
Jika kita melihat paragraph kelima, berita tersebut diawali dengan kata ‘Sebelumnya’. Kemudian menceritakan banyaknya rumah yang terendam beserta lokasi-lokasi banjir.
Dari
hal itu kita bisa mengetahui bahwa interaksi wartawan dengan Aher adalah ketika
banjir sudah terjadi. Dengan informasi itu, maka, pemaknaan bahwa Aher
menghadapi banjir adalah dalam fase penanggulangan bencana, bukan dalam tahap
antisipasi.
Kita
tidak perlu jadi sarjana teknik sipil, ahli fisika, atau anggota tim SAR, untuk tahu bahwa dalam fase
penanggulangan banjir, agar air surut, adalah sangat wajar adanya harapan agar
hujan tidak turun, tidak deras, atau tidak lama.
Mana
ada korban banjir yang ingin cepat surut tapi berharap hujan turun. Silakan
cari. (ter-Tere Liye). :)
Ketika konteksnya adalah hujan, maka Aher sudah benar
dengan tidak mengaitkannya dengan manusia atau peralatan, melainkan Tuhan. Entah
dalam sudut pandang apa komentar seperti ini dianggap salah, tidak baik, atau
tidak keren?
Lalu kenapa ada orang yang sampai menganggap itu sebuah
hal yang ‘gila’ atau ‘memalukan’? Selain karena abai terhadap detail tadi, juga
karena bahwa setiap berita memilki angle. Wartawan, Editor, Pimred, sampai
pemilki perusahaan media bisa menentukan apa yang perlu disampaikan atau tidak.
Semua komunikator punya efek yang ingin dicapai bukan?
Selain media yang punya tujuan dari semua beritanya,
penerima berita juga tentu memiliki tujuan dalam meneruskan berita (dan itulah
kenapa saya menyertakan Pilkada Jakarta pada judul tulisan ini, hahahay) .
Sangat wajar jika dari berita ini, maka, terbagilah umat kedalam beberapa
golongan, setidaknya:
Orang
yang membenci partai pengusung Aher (saya sebut inisialnya saja, yaitu, PKS).
Adalah sangat wajar jika berita ini menjadi peluru untuk menunjukan betapa
payahnya kader mereka. Dibanding, dibanding, dibanding siapa ayo? :D
Tim
sukses dan pemilih calon lain ketika Pilgub Jawa Barat, yang belum move on.
Sangat cocok untuk menjadikannya sebagai bahan sindiran, betapa mereka yang
telah memilih Aher, telah salah pilih.
Juga
para pendukung Aher, baik partai atau perseorangan, bisa juga menjadikan berita
itu sebagai info yang menunjukan bahwa pilihan mereka tepat, karena gubernur begitu
tawakal dan selalu ingat Tuhan.
Dan
yang tak ketinggalan adalah mereka sedang giat-giatnya menunjukan dukungan
terhadap bakal calon gubernur DKI Jakarta selanjutnya, yang bernama (ah, nggak
usah disebut, namanya nggak ada di judul sih), dan menjadikan tafsir berita
tadi sebagai perbandingan.
Dan
tentu bisa juga gabungan dari sosok-sosok di atas.
Ah,
Gung, elu sok tau, bawa-bawa konteks logika waktu segala. Teori!
Eh,
saya tuh bukan modal tampang doang, tapi menyertakan tautan video juga.
Ditonton ya. Di situ Aher juga berkomentar tentang usaha menghadapi banjir. Memang
banjir sudah terjadi. Tapi, dia bicara dalam konteks antisipasi. Dan dalam fase itu, dia tidak berharap Tuhan
tidak menurunkan hujan sekaligus kok.
Hikmah
dalam bersosial pada kasus berita ini bagi saya adalah bawah kita bisa saja
menyamarkan kesukaan atau kebencian, tapi keadilan atau kezaliman selalu menggeliat
hingga tampak kepermukaan.
Ada
yang ingat syair Iwan Fals yang bertanya ‘Apakah selamanya politik itu kejam?
Apakah selamanya dia datang ‘tuk menghantam?’ Ataukah memang itu yang sudah
digariskan? Menjilat, menghasut, menindas, memperkosa hak-hak sewajarnya’?.
Tadinya saya pikir itu hanya tentang politkus yang terlbat langsung dalam
politik. Ternyata orang-orang yang sekadar mendukung pun bisa sama buasnya.
Rabu, 17 Februari 2016
Pemikiran: ISU LGBT
Saya rasa tidak cocok paduan legalisai dengan LGBT.
Dua kata itu kok kalau digabungin jadi bikin nggak sreg, kecuali huruf T
(transgender).
Karena LGB itu kan orientasi seksual, sedangkan transgender bisa dikatakan sebuah proses selain juga keadaan (yang telah berubah).
Jadi, kata legalisasi terasa kurang cocok berdampingan dengan LGB. Karena, apa yang mau dilegalisasi dari sebuah orientasi?
Yang bisa dipermasalahkan itu adalah perilaku seksual. Ini relevan dengan kata legal/ilegal.
Jadi, penolakan LGB harusnya menekankan pada prilaku seksual dan atau 'pernikahan'.
Dalam Islam, bukan orientasi yang dihukumi, tapi perilaku.
Saya pribadi memandang orientasi seksual seperti banyak hal lain. Makanan contohnya. Ada daging ayam, sapi, babi, kodok, bayam, wortel. Semua ciptaan Allah. Tapi tidak semua diridhai Allah untuk dimakan, meski bisa dimakan.
Juga minuman. Ada susu, jus jeruk, mangga, apel, miras, amer, aput, nutrisari, orson. Semua bisa diminum, tapi tak semua diridhai sebagai minuman.
Begitu juga orientasi seksual. Ada hetero, homo, dan bi. Perilaku sekusal juga banyak. Ada nikah, zinah, lacur, incest, merkosa, selfservice, pedofil, sampai sama binatang. Tidak semua cara yang diridhaiNya.
Saya tak berkapasitas untuk menyatakan apakah orientasi seksual sejenis sesuatu yang dari sananya atau terbentuk lingkungan. Yang pasti itu ujian, yang pasti itu bisa dirubah, karena banyak contohnya. Kalau ada pertanyaan Kenapa saya terlahir homo? Karena si saya mampu mengatasi ujian kehomoan. Ujian tak lebih dari kadar kemampuan, bukan?
Ujian memang banyak macam. Ada yang diuji lewat orientasi seksual, ada yang lewat keterbatasan fisik, ada yang diuji dengan kemiskinan, ada juga yang lewat kekayaan. Ada ujian lewat kecantikan, ketampanan, (dan sepertinya saya diuji dalam hal ini), dan lain sebagainya. Macam-macam dah ya.
Karena LGB itu kan orientasi seksual, sedangkan transgender bisa dikatakan sebuah proses selain juga keadaan (yang telah berubah).
Jadi, kata legalisasi terasa kurang cocok berdampingan dengan LGB. Karena, apa yang mau dilegalisasi dari sebuah orientasi?
Yang bisa dipermasalahkan itu adalah perilaku seksual. Ini relevan dengan kata legal/ilegal.
Jadi, penolakan LGB harusnya menekankan pada prilaku seksual dan atau 'pernikahan'.
Dalam Islam, bukan orientasi yang dihukumi, tapi perilaku.
Saya pribadi memandang orientasi seksual seperti banyak hal lain. Makanan contohnya. Ada daging ayam, sapi, babi, kodok, bayam, wortel. Semua ciptaan Allah. Tapi tidak semua diridhai Allah untuk dimakan, meski bisa dimakan.
Juga minuman. Ada susu, jus jeruk, mangga, apel, miras, amer, aput, nutrisari, orson. Semua bisa diminum, tapi tak semua diridhai sebagai minuman.
Begitu juga orientasi seksual. Ada hetero, homo, dan bi. Perilaku sekusal juga banyak. Ada nikah, zinah, lacur, incest, merkosa, selfservice, pedofil, sampai sama binatang. Tidak semua cara yang diridhaiNya.
Saya tak berkapasitas untuk menyatakan apakah orientasi seksual sejenis sesuatu yang dari sananya atau terbentuk lingkungan. Yang pasti itu ujian, yang pasti itu bisa dirubah, karena banyak contohnya. Kalau ada pertanyaan Kenapa saya terlahir homo? Karena si saya mampu mengatasi ujian kehomoan. Ujian tak lebih dari kadar kemampuan, bukan?
Ujian memang banyak macam. Ada yang diuji lewat orientasi seksual, ada yang lewat keterbatasan fisik, ada yang diuji dengan kemiskinan, ada juga yang lewat kekayaan. Ada ujian lewat kecantikan, ketampanan, (dan sepertinya saya diuji dalam hal ini), dan lain sebagainya. Macam-macam dah ya.
Tapi memang manusia banyak macamnya. Ada yang simplisiti, asal teman
senang, yang penting gue nggak, ada juga yang menahan diri untuk selalu
membenarkan. Yang pasti, teman baik tak ingin temannya celaka.
Jumat, 06 November 2015
Cerkil: Setia
Si Germo mengajak Joni ke lantai dua. Menunjukan jajaran ruang kaca yang
dipenuhi wanita. Tak kurang, Si Germo perlihatkan katalog wanita sambil
bertanya, "Abang mau yang kayak gimana?"
"Aku mencari yang setia." jawab Joni.
"Aku mencari yang setia." jawab Joni.
Jumat, 30 Oktober 2015
Diary: Bukan Basa-Basi
Judulnya mirip tagline produk racun zaman dulu ya. Bukan basa-basi.
Ini memang tentang apa yang (tadinya) saya anggap basa-basi. Kejadiannya Kamis kemarin, selesai istirahat makan dan hendak kembali masuk kantor, saya berpapasan dengan OB di parkiran. Saya pun berbasa-basi dengan bertanya, "Kemana, Ko?"
"Beli lem." jawabnya.. Pertanyaan kemana memang seringkali dijawab dengan tujuan, bukan tempat. Sudah biasa itu. Saya berusaha menepis prasangka buruk kalau selama ini Eko suka mabok lem. Tapi masalahnya bukan dua hal itu, melainkan tentang basa-basi bertanya "kemana?" yang ternyata bukan basa-basi. Saat itulah saya membuktikannya. Karena setelah saya masuk ke lobby hendak naik tangga ke lantai dua, seseorang admin bertanya kepada saya, "Mas, lihat Eko, nggak?"
"Baru aja keluar, Mbak. Beli lem katanya."
Rasanya nikmat sekali bisa menjawab sesuatu yang menjadi pertanyaan seseorang. Bentuk kecil manfaat diri untuk orang lain. Bukankah sebaik-baiknya manusia adalah yang banyak manfaatnya bagi orang lain? Dan saya bisa menjawab itu karena saya bertanya sebelumnya. Kalau sebelumnya saya tidak berbasa-basi pada Eko, cuma senyum, atau malah cuek, tentu saya tak bisa memberi informasi apa-apa pada Mbak Admin. Padahal, kalau seseorang mencari seseorang, tentu ada perlu.
Jadi, ternyata, bertanya kemana itu bukan basa-basi. Selain bentuk kehangatan, itu juga menjadi informasi yang berguna.
Kalau lagi lewat naik motor kadang ketemu teman yang menyapa lalu bertanya.
"Gung...!"
"Woy!"
"Kemana?"
"Asnibasbjgnlkasd..ke depan..."
Padahal pertanyaan biasa, tapi kenapa suka bikin kagok ya?
Kalau lagi lewat naik motor kadang ketemu teman yang menyapa lalu bertanya.
"Gung...!"
"Woy!"
"Kemana?"
"Asnibasbjgnlkasd..ke depan..."
Padahal pertanyaan biasa, tapi kenapa suka bikin kagok ya?
Kamis, 29 Oktober 2015
Tips: Diwawancara
Kali ini saya akan berbagi tips untuk Anda yang sekiranya berkesempatan diwawancara oleh wartawan televisi ketika terjadi liputan. Entah pejabat, pengusaha, pedagang, mahasiswa, pelajar, polisi, sampai tersangka pencuri kolor, tak lepas dari kesempatan wawancara, ditanya, dimintai keterangan, dimintai pendapat, atau dimitai kesaksian.
Mungkin terbayang bahwa wawancara itu hal mudah, tinggal bicara apa adanya, adanya apa, sesuai dengan fakta, sesuai dengan yang dirasa. Sayanganya masih banyak yang abai terhadap konteks dari sebuah wawancara televisi, yaitu proses tayang.
Bagi yang mulai penasaran dengan maksud saya, yuk kita simak tips menjadi narasumber berikut ini:
1. Tak perlu pembukaan. Durasi tayang sangat berharga untuk televisi, jadi tiap detik sangat berarti. Anda harus singkat, jelas, dan padat. Saya pernah ngedit bagian wawancara yang narasumbernya salam dulu, terus ucapan terimakasih, baru jawab. Bukan meremehkan ramah-tamah, tapi ini bukan pidato yang biasanya waktu dan tempat dipersilakan oleh MC khusus untuk Anda.
2. Jangan nyerocos. Ini bukan tentang kecepatan bicara, atau emosi yang meledak-ledak ketika bicara. Nyerocos dalam hal ini adalah tidak mengakhiri kalimat dengan intonasi yang tepat atau bicara satu kalimat namun terburu-buru untuk menyambungnya dengan kalimat lain. Kalau versi tulisan, kalimat Anda seharusnya pakai titik, tapi malah dipaksa pakai koma, atau bahkan tanpa tanda baca. Atau sebenarnya sudah berhenti karena titik, tapi terlalu cepat menyambungnya, jadi titiknya terdengar percuma. Nah, kalau dikaitkan denga proses tayang, ini akan menyulitkan editor dalam memotong bagian ternyambung dengan naskah. Sebenarnya editor sudah tau kalimat mana yang mesti diambil, tapi karena Anda mengakhirinya dengan gantung, jadi kurang sedap didengar.
Anda mungkin pernah menonton berita yang di bagian wawancaranya narasumbernya seperti masih akan bicara tapi gambar dan suaranya sudah hilang. Mulutnya sudan terlihat mangap, tapi gambar langsung berganti. Nah, ini yang saya maksud dengan kurang sedap.
3. Pengertian akan kebisingan. Jika Anda mendengar suara berisik, seperti motor dengan knalpot racing lewat, atau suara orang lain yang cuku keras, Anda bisa mengulang dari bagian tertentu, atau Anda ajak reporter untuk mencari tempat sepi. Sebenarnya reporter harus lebih aktif, tapi kadang pengertian narasumber juga sangat dibutuhkan.
4. Anggap reporter adalah pemirsa. Jadi jangan menganggap reporter itu kurang kerjaan, karena menanyakan hal yang ia lihat dan dengar sendiri di TKP. Reporter tetap akan bertanya meski sudah tahu, karena materi rekam dia adalah untuk permirsa, bukan dirinya. Jadi, hindar berkata "Seperti Anda lihat sendiri...." atau "Kan tadi kamu lihat....", atau "Seperti yang sudah saya sampaikan dalam pidato tadi....." atau "Lihat sendiri kan...."
5. Percaya Diri. Saya beberapa kali dibuat bingung, dengan tingkah orang yang diminta wawancara. Ada saja yang menghindar. Ada yang menunjuk orang lain. Biasanya sambil mesem-mesem, senyum malu-malu macan. Sampai ada yang seperti berusaha lari dari sorotan kamera, padahal bukan liputan kriminal, esek-esek, judi, atau narkoba. Cuma meminta opini. Malah sampai ada ibu-ibu yang pas sudah direkam, dia malah bilang "Nih, dia aja nih, saya mah jelek." Bhehehe. Jelek tidaknya mah sudah bisa dilihat, tak perlu klarifikasi. Ini kah tentang berita, bukan muka. Kalau memang benar-benar menganggap muka sendiri adala aib, titip pesan saja ke reporter, nanti mukanya tolong diblur. Dengan senang hati kami sebagai editor akan melakukannya. Jadi, biasakan santai saja di depan kamera.
Demikian tips diwawancara jika Anda menjadi narasumber. Kalau ada tambahan atau kurangan, silakan.
Mungkin terbayang bahwa wawancara itu hal mudah, tinggal bicara apa adanya, adanya apa, sesuai dengan fakta, sesuai dengan yang dirasa. Sayanganya masih banyak yang abai terhadap konteks dari sebuah wawancara televisi, yaitu proses tayang.
Bagi yang mulai penasaran dengan maksud saya, yuk kita simak tips menjadi narasumber berikut ini:
1. Tak perlu pembukaan. Durasi tayang sangat berharga untuk televisi, jadi tiap detik sangat berarti. Anda harus singkat, jelas, dan padat. Saya pernah ngedit bagian wawancara yang narasumbernya salam dulu, terus ucapan terimakasih, baru jawab. Bukan meremehkan ramah-tamah, tapi ini bukan pidato yang biasanya waktu dan tempat dipersilakan oleh MC khusus untuk Anda.
2. Jangan nyerocos. Ini bukan tentang kecepatan bicara, atau emosi yang meledak-ledak ketika bicara. Nyerocos dalam hal ini adalah tidak mengakhiri kalimat dengan intonasi yang tepat atau bicara satu kalimat namun terburu-buru untuk menyambungnya dengan kalimat lain. Kalau versi tulisan, kalimat Anda seharusnya pakai titik, tapi malah dipaksa pakai koma, atau bahkan tanpa tanda baca. Atau sebenarnya sudah berhenti karena titik, tapi terlalu cepat menyambungnya, jadi titiknya terdengar percuma. Nah, kalau dikaitkan denga proses tayang, ini akan menyulitkan editor dalam memotong bagian ternyambung dengan naskah. Sebenarnya editor sudah tau kalimat mana yang mesti diambil, tapi karena Anda mengakhirinya dengan gantung, jadi kurang sedap didengar.
Anda mungkin pernah menonton berita yang di bagian wawancaranya narasumbernya seperti masih akan bicara tapi gambar dan suaranya sudah hilang. Mulutnya sudan terlihat mangap, tapi gambar langsung berganti. Nah, ini yang saya maksud dengan kurang sedap.
3. Pengertian akan kebisingan. Jika Anda mendengar suara berisik, seperti motor dengan knalpot racing lewat, atau suara orang lain yang cuku keras, Anda bisa mengulang dari bagian tertentu, atau Anda ajak reporter untuk mencari tempat sepi. Sebenarnya reporter harus lebih aktif, tapi kadang pengertian narasumber juga sangat dibutuhkan.
4. Anggap reporter adalah pemirsa. Jadi jangan menganggap reporter itu kurang kerjaan, karena menanyakan hal yang ia lihat dan dengar sendiri di TKP. Reporter tetap akan bertanya meski sudah tahu, karena materi rekam dia adalah untuk permirsa, bukan dirinya. Jadi, hindar berkata "Seperti Anda lihat sendiri...." atau "Kan tadi kamu lihat....", atau "Seperti yang sudah saya sampaikan dalam pidato tadi....." atau "Lihat sendiri kan...."
5. Percaya Diri. Saya beberapa kali dibuat bingung, dengan tingkah orang yang diminta wawancara. Ada saja yang menghindar. Ada yang menunjuk orang lain. Biasanya sambil mesem-mesem, senyum malu-malu macan. Sampai ada yang seperti berusaha lari dari sorotan kamera, padahal bukan liputan kriminal, esek-esek, judi, atau narkoba. Cuma meminta opini. Malah sampai ada ibu-ibu yang pas sudah direkam, dia malah bilang "Nih, dia aja nih, saya mah jelek." Bhehehe. Jelek tidaknya mah sudah bisa dilihat, tak perlu klarifikasi. Ini kah tentang berita, bukan muka. Kalau memang benar-benar menganggap muka sendiri adala aib, titip pesan saja ke reporter, nanti mukanya tolong diblur. Dengan senang hati kami sebagai editor akan melakukannya. Jadi, biasakan santai saja di depan kamera.
Demikian tips diwawancara jika Anda menjadi narasumber. Kalau ada tambahan atau kurangan, silakan.
Langganan:
Postingan (Atom)